Petani: Pahlawan yang Masih Hidup dalam Bayang Kemiskin
Setiap 24 September, bangsa ini merayakan Hari Tani Nasional. Peringatan ini bukan sekadar ritual tahunan, melainkan pengingat bahwa ada jutaan orang yang setiap hari bekerja keras memastikan kita tidak kelaparan. Petani adalah pahlawan pangan, meski sayangnya mereka seringkali diperlakukan seolah hanya bayangan dalam narasi pembangunan.
SIKAP
Beriandi Pancar
9/24/20252 min read
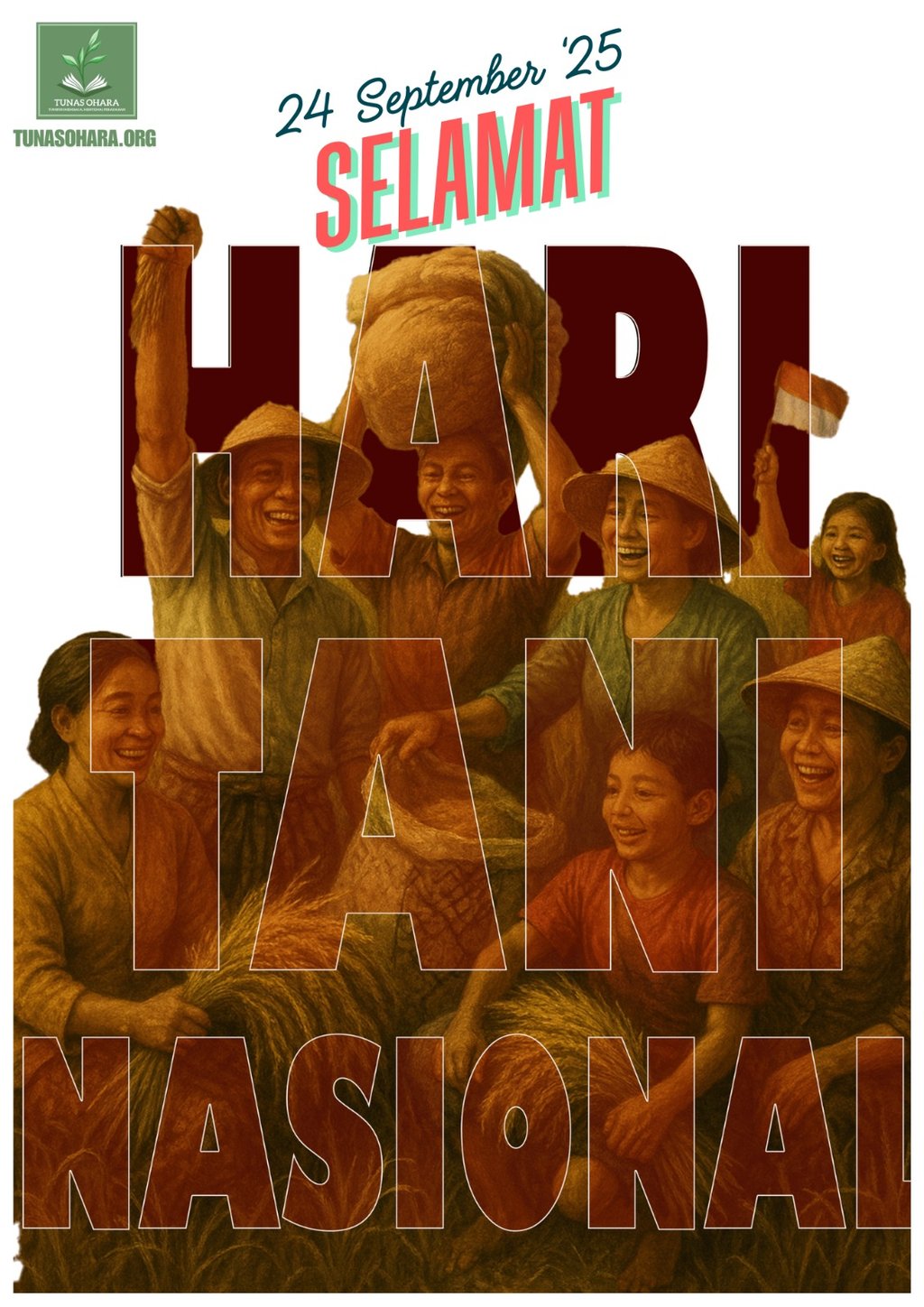
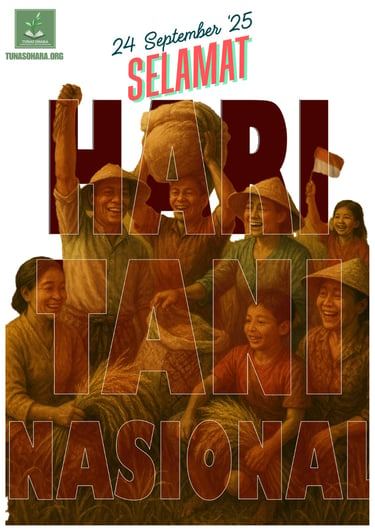
Setiap 24 September, bangsa ini merayakan Hari Tani Nasional. Peringatan ini bukan sekadar ritual tahunan, melainkan pengingat bahwa ada jutaan orang yang setiap hari bekerja keras memastikan kita tidak kelaparan. Petani adalah pahlawan pangan, meski sayangnya mereka seringkali diperlakukan seolah hanya bayangan dalam narasi pembangunan.
Menurut Sensus Pertanian BPS 2023, jumlah petani pengguna lahan di Indonesia mencapai 27,8 juta jiwa. Dari angka tersebut, sekitar 17,2 juta tergolong petani gurem, yakni mereka yang menggarap lahan kurang dari setengah hektar. Lahan yang sempit membuat hasil panen sulit mencukupi kebutuhan hidup, apalagi meningkatkan taraf ekonomi keluarga. Tak mengherankan bila laporan Kementerian Pertanian bersama BPS tahun 2024 menyebut hampir setengah penduduk miskin ekstrem di Indonesia bekerja di sektor pertanian. Ironinya, mereka yang memberi makan bangsa justru paling rentan jatuh dalam jurang kemiskinan.
Kondisi ini tidak berhenti di satu generasi. Beban kemiskinan yang menjerat petani berdampak langsung pada anak-anak mereka. Penelitian Universitas Negeri Makassar (2021) mencatat bahwa “anak-anak petani sering kali meninggalkan pendidikan formal demi membantu bekerja di ladang”, karena kondisi ekonomi keluarga, jarak sekolah yang jauh, dan minimnya fasilitas pendidikan di desa .
Data BPS Susenas 2023 juga menunjukkan adanya kasus nyata angka putus sekolah: di zona perdesaan, 1,12 % anak putus SD, 8,45 % putus SMP, dan hingga 26,06 % putus SMA sebelum menyelesaikan jenjang pendidikan . Ini berarti puluhan ribu bahkan ratus ribu anak dari kawasan pedesaan—banyak di antaranya berasal dari keluarga petani—berhenti sekolah sebelum mereka sempat membangun masa depan yang lebih baik.
Di sisi lain, negara kerap menekankan ambisi swasembada pangan. Program besar seperti Food Estate, yang digadang-gadang akan memperkuat ketahanan pangan, ternyata menimbulkan kontroversi. Laporan investigasi Pantau Gambut dan Mongabay (2024) menunjukkan banyak lahan proyek tersebut tidak produktif, bahkan sebagian beralih fungsi menjadi kebun sawit dan semak belukar. Lebih parah lagi, menurut catatan Aliansi Petani Indonesia (API, 2023), banyak petani lokal justru kehilangan akses tanahnya dan hanya diposisikan sebagai buruh tani dengan upah harian sekitar Rp50.000–70.000 per hari. Bayaran murah ini bahkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Dengan demikian, proyek ketahanan pangan tidak serta merta berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan petani.
Kontradiksi ini menunjukkan betapa timpangnya cara kita memandang petani. Di satu sisi, mereka diagungkan sebagai pahlawan pangan. Namun di sisi lain, kebijakan dan program besar seringkali mengabaikan suara mereka, bahkan menjauhkan mereka dari kesejahteraan yang layak. Hari Tani seharusnya bukan sekadar seremoni, melainkan momentum refleksi dan perbaikan arah.
Swasembada pangan tidak akan ada artinya jika petani tetap miskin, jika anak-anak mereka terus kehilangan kesempatan pendidikan, dan jika tanah yang mereka garap justru dikuasai pihak lain. Sudah saatnya kita mengubah paradigma: kedaulatan pangan harus dimulai dari kesejahteraan petani. Tanpa itu, peringatan Hari Tani hanya akan menjadi perayaan kosong tanpa makna.
Tunas Ohara
Tumbuh Membaca, Menyemai Peradaban
Kontak
© 2025. Hak Cipta dilindungi Tuhan yang Maha Esa


